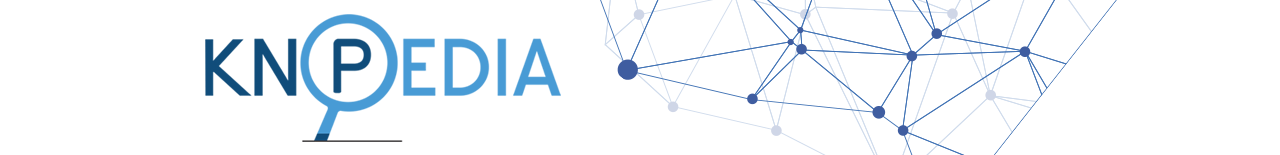Putra PM Siregar * & Ajeng Hanifa Zahra**
Hari-hari ini, hampir seluruh ruang pemberitaan media diisi dengan topik seputar Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau awam disebut Korona/Virus Korona. Sejak kasus pertama virus ini ditemukan pada November 2019 silam, jumlah kasus terus mengalami eskalasi yang signifikan. World Health Organisation (WHO) merilis data, sampai dengan tanggal 13 April 2020 pukul 07.00 GMT+7, tercatat 1.776.867 kasus COVID-19, termasuk diantaranya 111.828 angka kematian. Di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat bahwa sampai dengan tanggal 13 April 2020 pukul 12.00 WIB terdapat 4.557 orang dinyatakan positif COVID-19 dimana 399 diantaranya meninggal dunia dan 380 dinyatakan sembuh.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta bekerja/belajar dari rumah. Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
Khusus di Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Salah satu bentuk pembatasan yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta berupa penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/kantor dengan pengecualian bagi pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi (TI), keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari.
Imbas Covid-19
Imbauan kepada masyarakat untuk melakukan physical distancing, kampanye “#dirumahaja” serta langkah-langkah pembatasan aktivitas melalui sejumlah aturan yang diambil Pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk menekan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, physical distancing dan pembatasan aktivitas tersebut secara tidak langsung membuat aktivitas-aktivitas masyarakat di tempat umum, tempat perbelanjaan, destinasi wisata, dan perkantoran berkurang secara signifikan. Berkurangnya aktivitas masyarakat membuat ujian yang cukup berat bagi kegiatan ekonomi.
Berdasarkan Survei Sentimen Pasar Hotel & Restoran Indonesia terhadap Pengaruh Wabah COVID-19 pada bulan Maret 2020 (PHRI dan Howath HTL), tingkat okupansi hotel turun 25-50% dengan total pendapatan turun pada kisaran 25-50%. Demikian pula pada sektor restoran, total pendapatan turun 25-50%. Pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data bahwa per-tanggal 27 Maret 2020 profil risiko masih terjaga dengan Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2.79 %. Namun menurut Perry Warjiyo, risiko NPL tetap perlu diwaspadai karena perlambatan ekonomi membuat kinerja perusahaan dan UMKM menurun.
Peneliti Fornano & Wolf (Corona and Macroeconomic Policy, 2020), menyebutkan bahwa “the coronavirus outbreak will cause a negative supply shock to the world economy, by forcing factories to shut down and disrupting global supply chains”. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kemudian mengabstraksikan hasil penelitian Fornano & Wolf tersebut dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa pandemi COVID-19 ini diprediksi akan menyebabkan guncangan sisi penawaran-permintaan yang meliputi penurunan produksi barang – penurunan pendapatan – gelombang pemutusan hubungan kerja – penurunan daya beli – penurunan permintaan atas barang.
Lebih jauh, para pelaku usaha baik sebagai supplier, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen akan mengalami situasi yang kurang kondusif pada masa pandemik COVID-19. Bagi debitur, penurunan omset akibat berkurangnya permintaan akan berdampak pada kemampuan membayar kredit kepada kreditur, bahkan bisa mengakibatkan gagal bayar. Sehubungan dengan hal ini, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11/2020).
Menurut POJK No. 11/2020, Bank dapat memberikan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada debitur. Syaratnya, debitur dimaksud terkena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank (bank umum konvensional, termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah). Adapun jenis usaha debitur yang dapat diberikan stimulus adalah yang bergerak pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Namun, patut dicatat, kebijakan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan diserahkan kepada pihak Bank. Dalam hal ini, Bank yang akan melakukan self-assessment dengan pedoman yang paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak COVID-19. Lalu, bagaimana jika debitur tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank? Bagaimana terhadap pelaku usaha lain yang kegiatan usahanya terdampak COVID-19 namun tidak termasuk kriteria yang dimaksud dalam POJK No. 11/2020? Apakah, pelaku usaha dapat mengajukan restrukturisasi dengan alasan force majeure?
Beda Pendapat Soal Force Majeure
Menurut Black’s Law Dictionary, force majeur adalah “an event or effect that can be neither anticipated nor controlled”. Dalam hukum perdata materiil Indonesia, istilah force majeure memang tidak diatur secara tegas. Namun di dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa pihak dalam suatu perikatan tidak diwajibkan memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa (overmacht). Dari ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata dan Black’s Law Dictionary tersebut, terdapat benang merah yakni pihak tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal. Dalam konteks pandemi COVID-19, apakah keadaan memaksa (force majeure) dapat terpenuhi secara hukum? Atau, apakah klaim force majeure tetap harus merujuk pada perjanjian yang disepakati para pihak?
Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata tercantum di dalam Buku Ketiga tentang Perikatan - Bab I tentang Perikatan Pada Umumnya. Artinya, ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata sejatinya berlaku bagi para pihak dalam suatu perikatan dengan syarat, pertama, para pihak menundukkan diri bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagai governing law; dan kedua, para pihak tidak mengatur secara khusus mengenai klausula force majeure dalam perikatan.
Praktisi hukum, Ricardo Simanjuntak, berpendapat bahwa terlepas apakah para pihak dalam suatu perjanjian mengatur mengenai pandemi sebagai alasan force majeure, ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata tetap berlaku dan harus dipatuhi. Ricardo menambahkan, dalam konteks pandemi COVID-19, force majeure dapat diklaim karena para pihak tidak dapat memprediksi pandemi dan tidak memiliki contributory effect serta pandemi ini menjadi suatu halangan yang terjadi secara umum.
Sementara itu, sebagaimana dilansir World Oil, perusahaan besar China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) mengklaim pandemi COVID-19 sebagai alasan force majeure dan memberitahukan kepada Shell dan Total bahwa CNOOC tidak dapat menerima pengiriman LNG yang mereka kirim. Adapun alasan utama CNOOC, pandemi berdampak pada berkurangnya pekerja yang mencukupi di titik penerimaan sehingga mereka tidak dapat beroperasi secara normal. Namun, alasan force majeure tidak diterima oleh kedua perusahaan minyak tebesar di Eropa tersebur. The Economist (2020) menengarai hal ini dikarenakan sangat sulit untuk melemahkan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian kerjasama.
Pendapat lainnya Rahayu Ningsih Hoed, Senior Partner dari lawfirm ternama, berpendapat bahwa pandemi COVID-19 termasuk sebagai suatu keadaan kahar tergantung dari definisi keadaan memaksa (apabila ada) di dalam perjanjian. Menurutnya, jenis klausul keadaan memaksa terdiri dari 2 (dua) klausul, pertama, klausul tidak eksklusif dimana suatu pihak dapat mengklaim force majeure sepanjang adanya kondisi yang disetujui untuk berlakunya force majeure dan kedua, klausul ekskusif dimana keadaan memaksa terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian.
Pada praktiknya, para pihak dalam perjanjian akan mencantumkan klausula force majeure dan lazimnya ruang lingkup force majeure didefinisikan lebih rinci. Salah satu contoh klausula force majeure, sebagai berikut:
Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (force majeure), maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Pihak-Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.
Yang dimaksud dengan force majeure adalah kejadian-kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian.
Sebagai alternatif, ada juga klausula force majeure yang secara tegas meneyebutkan pandemi sebagai alasan force majeure. Misalnya, ketentuan force majeure yang ada dalam Syarat dan Ketentuan (Terms and Conditions) yang diberlakukan oleh salah satu perusahaan penyedia layanan pemesanan hotel dan tiket transportasi, sebagai berikut:
Kami tidak bertanggung-jawab ataupun menanggung kerugian Anda dalam hal Kami tidak dapat menyerahkan Produk atau memberi Layanan kepada Anda, akibat dari hal-hal yang terjadi akibat keadaan memaksa atau yang diluar kekuasaan Kami atau Mitra Penyedia Kami untuk mengendalikan, seperti, tapi tidak terbatas pada: perang, kerusuhan, teroris, perselisihan industrial, tindakan pemerintah, epidemik, pandemik, bencana alam, kebakaran atau banjir, cuaca ekstrim, dan lain sebagainya.
Berbeda dengan rumusan klausula force majeure yang sebelumnya, klausula force majeure di atas dengan jelas menyebutkan frasa “tindakan pemerintah, epidemik, pandemik, bencana alam, …”sehingga relatif lebih mudah dalam mengklaim adanya force majeure.
Strategi Klaim Force Majeure
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh para pelaku usaha dalam siklus supply-demmand tidak terkecuali bagi pemberi dan penyedia jasa serta kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, pengajuan klaim force majeure seyogianya dilakukan dengan semangat untuk bersama-sama memenuhi kewajiban masing-masing pihak dengan cara-cara terbaik.
Pengajuan klaim force majeure sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya jenis perjanjian dan karakter bisnis pelaku. Oleh karena itu, klaim implementasi force majeure dari satu kasus ke kasus yang lain mungkin saja berbeda (case by case basis). Ada beberapa pertimbangan dalam mengajukan klaim force majeure, diantaranya:
Pertama, klaim force majeure diajukan dengan iktikad baik dan sesuai tata cara pemberitahuan yang disepakati dalam perjanjian. Para pihak dalam suatu perikatan perlu memahami bahwa asas iktikad baik tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian, namun sejak persiapan perjanjian (pre-contract), pelaksanaan perjanjian (during the period of contract), dan penyelesaian sengketa (disputes settlement). Meskipun secara faktual terdampak pandemi COVID-19, pihak yang mengklaim force majeure harus dengan iktikad baik berusaha melakukan hal-hal yang dianggap patut dan wajar untuk tetap melaksanakan kewajiban atau paling tidak melakukan upaya utuk memitigasi risiko tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian. Kemudian terkait tata cara pemberitahuan, umumnya ditentukan bahwa pihak yang mengalami/terdampak force majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu sejak dampak tersebut dirasakan.
Kedua, klaim force majeure didasarkan pada rujukan hukum yang tepat. Pihak yang mengajukan klaim harus terlebih dahulu meneliti apakah bencana, pandemi atau tindakan pemerintah pemberlakuan aturan tertentu termasuk ruang lingkup force majeure yang diakomodasi dalam perjanjian. Apabila, klaim force majeure didasarkan pada adanya tindakan pemerintah, pihak yang mengklaim dianjurkan untuk membuktikan bahwa adanya tindakan pemerintah tersebut secara nyata berdampak pada kegiatan/aktivitas bisnisnya. Misalnya, dalam konteks Pembatasan Sosial Bersakala Besar yang diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta dan beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Pihak yang mengklaim harus dapat membuktikan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 dan Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Pergub Nomor 27 Tahun 2020 menyebabkan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pihak dimaksud harus meneliti apakah pembatasan aktivitas/kegiatan yang diatur dalam PSBB menghambat pelaksanaan kewajiban dan membuktikannya. Tidak hanya itu, Pihak yang mengklaim harus memperhatikan apakah kegiatan usahanya dikecualikan dari ketentuan PSBB tersebut. Sebagai pendukung argumentasi, pihak yang mengajukan klaim force majeure karena pandemi Covid-19 dapat menggunakan Kepres 12 Tahun 2020 sebagai penetapan pemerintah atas status pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Dalam konteks perpajakan, klaim dapat merujuk misalnya pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tahun 2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 yang menetapkan penyebaran Covid-19 dari tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 sebagai keadaan kahar. Pada prinsipnya, Pihak yang mengklaim harus dapat membuktikan secara patut bahwa adanya force majeure berdampak pada pemenuhan kewajiban serta dasar hukum yang sesuai dengan konteks hubungan hukum diantara para pihak.
Ketiga, klaim diajukan dengan maksud untuk merubah perjanjian dan bukan mengakhiri perjanjian. Penting untuk dipahami bahwa klaim adanya force majeure tidak serta merta menggugurkan kewajiban pihak tersebut. Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata bahkan hanya berkaitan dengan pembebasan atas kewajiban untuk mengganti rugi. Oleh karena itu, pada saat pengajuan klaim force majeure, pihak tersebut seharusnya telah menyiapkan alternatif perubahan perjanjian, misalnya berupa perubahan tenggat waktu pembayaran kredit/pembiayaan, penyesuaian kuantitas, kualitas barang/layanan, milestone kontrak maupun jadwal pelaksanaan layanan (delivery time). Apabila disepakati, perubahan perjanjian tersebut lebih baik dituangkan dalam akta notariil dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian awal.
Keempat, mengutamakan penyelesaian secara musyawarah serta tetap tunduk pada tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian. Dalam melakukan negosiasi perubahan perjanjian, para pihak harus sedapat mungkin mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan menghindari penyelesaian melalui litigasi. Dalam situasi saat ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak hanya memerlukan proses yang panjang tetapi juga kompleks. Dapat dibayangkan, berapa banyak potensi perkara wanprestasi akibat pandemi COVID-19 yang akan diselesaikan di pengadilan terlebih ditengah situasi pembatasan jarak/fisik saat ini.
Kelima, berkonsultasi dengan praktisi atau konsultan hukum mengenai opsi-opsi hukum yang dapat dilakukan. Tentu saja, pelaksanaan perjanjian tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis semata, melainkan juga aspek legal. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan praktisi/konsultan hukum yang diyakini dapat memberikan opsi hukum yang sesuai dengan kondisi para pihak.
Ditulis pada tanggal 14 April 2020.
* Pelaksana pada Subdirektorat Bantuan Hukum (Dit. Hukum & Humas)
** CPNS Kementerian Keuangan (Pegawai OJT pada Subdirektorat Bantuan Hukum)