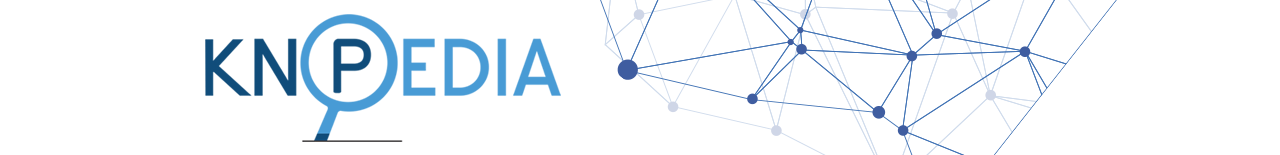Pernahkah kamu membuat story di Instagram tentang
pekerjaanmu? Atau pernahkah kamu sengaja bercerita betapa sibuknya dirimu di
media sosial agar dianggap pekerja keras oleh atasan dan rekan kerjamu? Atau
apakah kamu terus bekerja hingga hampir tidak memiliki waktu untuk diri
sendiri? Atau barangkali kamu pernah merasa takut tertinggal, cemas, atau
merasa insecure melihat teman-temanmu karirnya menanjak menuju puncak
sementara hidupmu terasa biasa-biasa aja? Inilah fenomena budaya gila
kerja yang kini menjadi tren, khususnya di kalangan anak muda. Apa sih
penyebabnya?
Transformasi dunia digital yang begitu pesat menuntut
pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Teknologi modern yang
digadang-gadang mampu memudahkan manusia di sisi lain terkadang justru membuat
pekerjaan kian bertambah, bahkan tak selalu membuat segalanya jadi lebih mudah.
Setiap individu berlomba mengejar kesuksesan, saling berpacu dalam lintasan
yang tak jarang diwarnai luka dan pengorbanan.
Media pun turut mengambil peran, baik media
sosial pribadi maupun media publik, dengan terus-menerus menayangkan kisah-kisah
sukses tokoh-tokoh ternama seperti Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark
Zuckerberg, Putri Tanjung, dan Nadiem Makarim. Tak hanya itu, melalui media sosial kita juga dapat melihat aktivitas
teman-teman kita, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau capaian
teman-teman kita. Sinergi kedua hal tersebut bersama-sama saling memengaruhi
seseorang untuk terus merasa dirinya kurang produktif, untuk terus bekerja
keras tanpa mempedulikan kesehatannya, hingga akhirnya terjebak dalam lingkaran
budaya gila kerja yang disebut hustle culture.
Hustle Culture = Workaholism
Secara etimologis, istilah hustle culture berasal
dari kata Bahasa Inggris, hustle, yang berarti antara lain aksi energik,
mendorong seseorang agar bisa bergerak lebih cepat secara agresif, dipadukan dengan kata culture yang berarti
budaya. Sedangkan
definisi hustle culture menurut pakar psikologi adalah budaya yang
membuat seseorang menganut workaholism atau gila kerja (Setyawati,
2020). Istilah workaholism diperkenalkan pertama kali oleh Wayne Oates
dalam bukunya yang berjudul Confessions of a Workaholic : the Facts About Work
Addiction pada tahun 1971. Kini tren hustle culture dimaknai sebagai suatu
keadaan bekerja terlalu keras dan mendorong diri sendiri untuk melampaui batas
kemampuan hingga akhirnya menjadi gaya hidup. Dengan kata lain, tiada hari
tanpa bekerja, hingga tak ada lagi waktu untuk kehidupan pribadi. Budaya gila kerja inilah yang telah menjadi standar bagi sebagian orang
untuk mengukur hal-hal seperti produktivitas dan kinerja.
Dalam dunia yang begitu kompetitif ini,
produktivitas dijunjung tinggi dan budaya gila kerja cenderung diapresiasi. Konstruksi
sosial masyarakat berpandangan bahwa tolok ukur kesuksesan
hidup seseorang adalah jabatan dan kondisi finansial yang baik. Keadaan ini
diperparah dengan tren memamerkan kesibukan di media sosial yang menjangkiti
para kawula muda. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Robinson (2019),
sebanyak 45 persen dari para pengguna sosial media gemar mengunggah post tentang
betapa sibuknya mereka seperti saat mereka lembur, saat dikejar banyak deadline,
target, dan semacamnya semata untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pekerja
keras dan pegawai yang berdedikasi. Pengaruh sosial media ini akhirnya
mendorong para pengguna untuk berpikir bahwa bekerja terlalu keras adalah hal
yang keren. Imbasnya, timbul efek bola salju karena para pengguna media sosial
lainnya enggan merasa tertinggal sehingga mereka pun menunjukkan kesibukannya
dengan harapan mendapatkan atensi dari lingkungan media sosial. Faktor inilah
yang mendorong maraknya fenomena hustle culture.
Kerja Keras Tak Selalu Positif
Pada dasarnya, bekerja keras merupakan hal
positif, akan tetapi ketika seseorang terlalu mementingkan pekerjaannya hingga
tak pernah beristirahat, saat itulah akan timbul masalah. Kebiasaan ini tak
baik bagi kesehatan baik fisik maupun mental. Pekerja yang menganut hustle
culture cenderung mengabdikan diri hanya untuk bekerja, jarang
beristirahat, kurang tidur, dan seringkali memotivasi diri sendiri untuk terus mengabaikan
rasa sakit dengan tetap bekerja. Orang yang terjebak dalam hustle culture
seringkali tidak menyadari hal ini karena budaya tersebut telah tertanam dan
menjadi hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Akibatnya mereka tidak dapat lagi
mengenali respons negatif tubuh yang menginginkan istirahat saat diperlukan.
Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat berbahaya bagi tubuh.
Barangkali sebagian orang akan
menyangkal bahwa hustle culture berbahaya bagi kita. Anggapan
tersebut tentu tidak sepenuhnya salah. Namun, sebagai manusia yang memiliki limit,
tentu kita harus mendahulukan kesehatan fisik dan mental kita di atas
segalanya. Kesuksesan tak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan.
Berdasarkan
penelitian yang dipublikasikan oleh Current Cardiology Reports, dari data observasi 740.000
pekerja yang tidak memiliki penyakit kardiovaskular bawaan, ditemukan fakta
bahwa mereka yang bekerja lebih dari 55 jam per minggu memiliki peningkatan
risiko penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular, seperti penyakit jantung
koroner. Selain
itu, kerja lembur juga ditemukan dapat berkontribusi terhadap resistensi
insulin, aritmia, hiperkoagulasi, diabetes, bahkan stroke.
Perubahan sistem kerja pada masa pandemi
juga turut mempengaruhi panjangnya jam kerja yang berimbas pada kesehatan
mental para pekerja. Dilansir dari katadata.com, survei terbaru terkait sistem
WFH menunjukkan bahwa sebanyak 68 persen pekerja merasakan kelelahan mental
lebih dibandingkan bekerja dari kantor dan 60 persen merasakan jam kerja
bertambah dibandingkan saat bekerja di kantor. Dalam kajian terpisah, World
Economy Forum mendapatkan tiga kesimpulan dari adanya sistem WFH selama
pandemi, yaitu waktu yang dihabiskan untuk bekerja menjadi lebih panjang (naik
48,5 menit), email yang terkirim lebih banyak (naik lima persen), dan waktu
antara kehidupan pribadi dengan waktu kerja semakin baur.
Lantas, apakah bertambahnya jam kerja
tersebut berhasil meningkatkan produktivitas pekerja? Faktanya, penelitian yang
dilakukan oleh John Pencavel menunjukkan bahwa orang yang bekerja terlalu lama
tidak serta-merta akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Menurut
analisis Pencavel, justru bekerja lebih dari 48 jam per minggu membuat
produktivitas turun. Individu yang bekerja hingga 70 jam seminggu bahkan hanya
dapat menyelesaikan jumlah pekerjaan yang sama dengan individu yang bekerja
hingga 55 jam per minggu. Bekerja tanpa henti akan mengurangi waktu tidur dan
mengakibatkan kelelahan sehingga kualitas produktivitas justru menurun. Dengan
kata lain, alih-alih mendapatkan hasil optimal, yang didapatkan hanya lelah
semata.
Sementara itu, mengutip Dr. Jeanne
Hoffman, psikolog pada Fakultas Kedokteran University of Washington, bekerja
keras terlalu lama juga dapat menumpulkan kreativitas. Ia mengatakan bahwa
bekerja lebih dari 50 jam per minggu justru menurunkan tingkat kreativitas. Di
sisi lain, para pekerja yang memiliki jam kerja lebih panjang juga cenderung
mengabaikan keluarga dan kehidupan pribadinya. Padahal, dengan menghabiskan
waktu bersama keluarga maupun teman dapat mengurangi tingkat stres akibat
pekerjaan. Kebahagiaan dapat meningkatkan kreativitas dan menghasilkan energi positif.
Tak hanya merugikan diri sendiri,
penganut hustle culture ini juga merugikan rekan kerjanya. Mereka cenderung memaksa orang lain
untuk bekerja dengan intensitas yang tinggi seperti mereka. Seringkali pekerja
yang gila kerja memberi pekerjaan pada rekannya pada jam istirahat atau hari
libur. Perilaku semacam ini dapat menimbulkan perselisihan antar rekan satu tim
hingga berakibat buruk pada produktivitas tim. Tentunya, kita tidak
menginginkan dampak-dampak buruk itu terjadi kan?
Solusi Mengatasi Hustle Culture
Agar tren hustle culture tidak sampai
memberi dampak buruk bagimu, berikut ini adalah beberapa tips atau cara yang
bisa kamu lakukan untuk menghadapi hustle culture.
Yang pertama, kamu harus sadar terhadap
keadaan. Saat kamu mulai merasa terlalu lama bekerja dan tubuhmu mulai
memberikan respons negatif seperti kelelahan, kamu harus segera sadar dan
beristirahat. Batasan dan kemampuan orang berbeda-beda. Oleh karena itu, kamu
harus memahami dan menetapkan batasan untuk dirimu sendiri.
Buatlah jadwal perencanaan dengan baik
agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan dan deadline. Jangan lupa jadwalkan
istirahat atau bahkan liburan di sela-sela kesibukanmu. Dengan perencanaan yang
efektif, kamu akan menjadi lebih produktif dan terhindar dari kelelahan.
Salah satu ciri orang yang menganut hustle
culture adalah menetapkan target yang tidak realistis. Memang tidak ada
salahnya bersikap ambisius dan menetapkan target tinggi. Namun, kamu juga harus
bisa membuat target-target yang realistis dan sesuai dengan keinginan serta
keadaanmu sendiri. Kumpulan langkah-langkah kecil tetapi terukur dan mudah
dicapai lebih baik daripada langkah besar yang tak mampu diraih.
Selain itu, kamu juga sebaiknya berhenti
membanding-bandingkan pencapaianmu dengan orang lain. Mudah bagi kita untuk
merasa inferior, merasa terus kurang, dan jadi berpikir harus bekerja lebih
agar bisa seperti mereka. Akan tetapi, setiap orang memiliki latar belakang
yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Kamu adalah
bintang utama dalam film hidupmu sendiri, bukan orang lain. Jadi, tidak ada
faedahnya membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain.
Itulah tips yang bisa kamu lakukan agar
terhindar dari hustle culture dan menerapkan gaya kerja yang sehat.
Memang tidak ada yang salah dengan bekerja keras, melakukan pekerjaan sebaik
mungkin akan memberikan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Akan tetapi, jangan
sampai kita melupakan fakta bahwa kita adalah manusia yang memiliki aspek
kehidupan pribadi dan kehidupan sosial selain kehidupan pekerjaan. Seperti roda
gigi yang saling bertaut dan mendorong satu sama lain, segala aspek dalam
hidupmu pun harus berjalan secara seimbang demi kehidupan yang bahagia.
Bekerjalah untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja.
Penulis: Indah Retnowati (Seksi Hukum dan Informasi)
Referensi:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hustle
Afrina Afra, “The Truth
About the Hustle Culture”, Taylors University, 2021, https://university.taylors.edu.my/en/campus-life/news-and-events/news/the-truth-about-the-hustle-culture.html
John Pencavel, ‘The Productivity of Working
Hours’, The Economic Journal, 125(589), 2015, doi:10.1111/ecoj.12166.
BBC,
“Toxic Productivity during lockdown”, Youtube, 2020, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=r-rht7kCASo
Unair News, “Preventing Toxic Productivity amid pandemic”, UNAIR NEWS, 2021, http://news.unair.ac.id/en/2021/07/14/preventing-toxic-productivity-amid-pandemic
Alfons Yoshio, “Survei:
Work from Home Picu Jam Kerja Bertambah dan Kelelahan Mental”, Katadata, 2020, https://katadata.co.id/ariemega/berita/5fa7cf815a0e8/survei-work-from-home-picu-jam-kerja-bertambah-dan-kelelahan-mental.
Emily Boynton, “What is Hustle Culture and How Does it Impact
Your Health?”, Right As Rain by UW Medicine, 2020, https://rightasrain.uwmedicine.org/life/work/hustle-culture